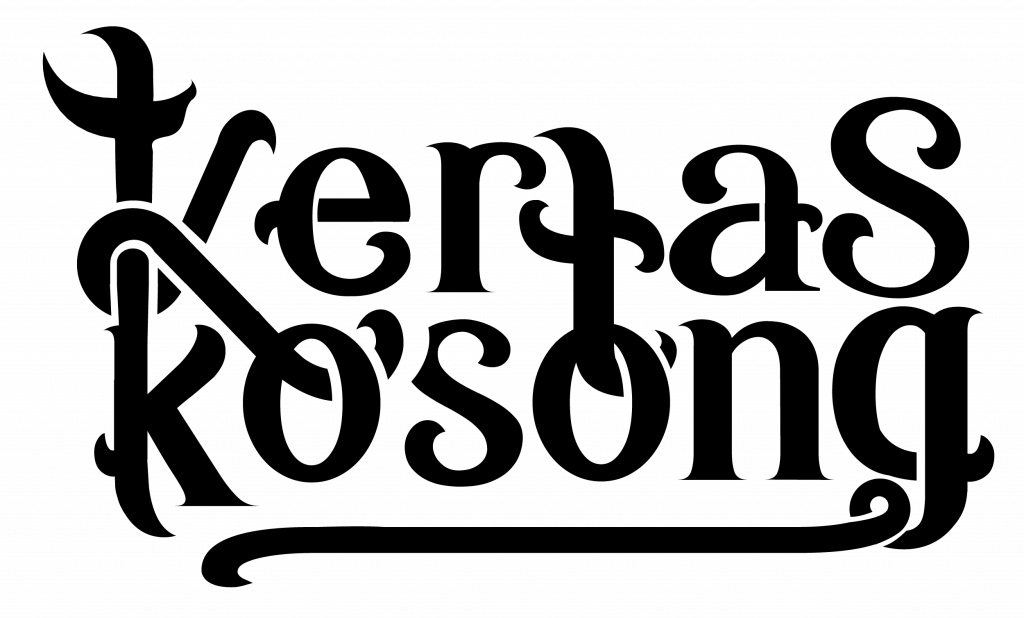Onde-Onde Terakhir & Budaya Malu
Nasionalisme ditanamkan dengan kisah-kisah perjuangan. Memupuk cinta tanah air ditambah lagi dengan menyiramkan bermacam mitos ke dalam kepala anak-anak. Bahkan jajanan bisa menjadi narasi menguatkan karakter generasi.
Saya ingat “doktrin” dari Pak Kastolani. Dia adalah guru yang piawai dalam story telling saat saya berseragam merah putih. Kisah-kisahnya menetap pada ingatan. Mirip bekas luka di betis saya akibat bermain bakar-bakaran plastik. Katanya, sehebatnya-hebatnya orang Belanda, tetap heran tatkala melihat onde-onde. Mereka tak habis pikir, bagaimana cara menempelkan wijen sedemikan rupa sehingga tampilan kulit onde-onde bisa tampak harmonis lagi estetik. Apakah wijen yang bernama latin sesamum indicum harus ditempelkan satu persatu.
Dengan jenaka, Pak Kastolani melanjutkan dongengnya. Si Belanda kebingungan bagiamana caranya memasukkan kacang hijau nan legit ke dalamnya. Seperti cara Tuhan yang diam-diam –saat manusia tertidur ngorok– memasukkan air dalam batok kelapa. Tentu saja itu bukan terakhir kali, saya mendengar celoteh onde-onde menjadi sumber kebanggaan bangsa.
Lepas dari itu, onde-onde sampai saat ini menjadi salah satu jajajan tradisional favorit saya. Sewaktu kecil, nyaris akses terhadap jajanan adalah kemewahan. Maka, salah satu momen penting adalah ketika datang tamu-tamu ayah saya. Lalu ibu memberi suguhan dengan lebih dulu bergegas membeli jajanan di warung terdekat.
Tentu saja, saya seperti halnya kakak-adik saya menunggu saat si tamu pamitan. Untuk kemudian menginvasi sisa-sisanya. Kurang lebih mirip Luhansk dan Donetsk yang diakui sebagai hak milik Rusia. Demi satu biji onde-onde, saya rela mengorbankan waktu bermain hilang. Menunggu tamu pergi dengan bersabar, asal jatah sebongkah kue bisa tersambar.
Untung saja, hampir tak pernah ada tamu yang benar-benar menandaskan kue-kue jamuan di meja. Seingin-inginnya menyantap makanan suguhan, memang harus ada yang disisakan. Saya kira sopan santun ini berlaku universal, di dunia Timur bahkan di dunia Barat. Perlulah kita menyimpan malu. Selapar-laparnya kita, tetap ada kewajiban menolak untuk rakus.
Paling tidak harus ada tersisa satu onde-onde di piring. Minimal ada satu kue tertinggal di toples. Satu onde-onde adalah simpanan kekayaan, satu kue di piring adalah tabungan rasa malu. Coba bayangkan jika saat bersamaan ada dua orang yang serentak hendak merogoh makanan yang tinggal satu. Tabrakan keinginan akan berakibat malu. Menghabiskan jamuan tanpa menyisakan rasa malu berarti pula keserakahan.
Bagaimana jika ada anak-anak -seperti pengalaman saya waktu kecil- meneropong kue dari jauh. Setia menunggu tamu pergi untuk menikmati. Siapa tahu pula, ada si bibi yang tak sempat menikmati. Mungkin saja, ada seorang ibu yang tak sempat mencoba sebijipun onde-onde karena kesibukannya melayani tamu. Barangkali satu onde-onde adalah ” jatah preman” bagi si pemalu yang enggan berebut.
Rasa malu ini penting. Jika rasa malu ini tak tersisa, banyak orang yang kekenyangan, di lain tempat ada pula manusia berkekurangan. Malu membuat manusia berusaha menahan hasrat. Malu menjadikan manusia merampas saat orang lain lengah.
Makhluk Pemalu
Manusia disebut sebgai homo puppy. Manusia berwajah kemerahan karena malu. Sifat ini khas manusia dan ekpresi khas manusia. Kita adalah jenis makhluk yang peduli akan apa yang dipikir orang lain. Karenanya, kita mencoba saling percaya. Inilah modal untuk bekerjasama. Untuk alasan tertentu, inilah kenapa manusia kadang harus menyembunyikan ekpresinya. Kita tak mau ketahuan orang saat menatap mereka lama-lama. Pipi kita mudah berwarna kemerahan. Alis manusia bisa menunjukkan ekpresi. Maka itulah para bodyguard termasuk anggota paspampres suka menyembunyikan ekspresi dengan berkacamata hitam.
paling tidak di dunia ini- ada yang lebih berat dari dosa. Ialah rasa malu. Cap menjadi penjahat, kriminal, asusila, perampok, pembunuh akan melekat labelnya menjadi rasa malu yang menetap dan berkepanjangan. Sanksi sosial juga bisa terasa lebih kejam dari pada dipenjara sekian waktu.
Seorang laki-laki bereputasi hebat, bisa saja memesan hotel dan tidur dengan perempuan lain. Tanpa takut dosa. Tetapi bagaimana jika ketahuan? Jika itu cuma diketahui oleh istrinya mungkin masih bisa disimpan aibnya. Tetapi jika perbuatan itu diketahui banyak orang?
Kita diperlihatkan pula bahwa rasa malu ini terjun bebas. Ketika koruptor dipajang dengan rompi berwarna nyala masih pamer senyuman. Teringat dengan amarah publik dunia, khususnya publik Australia melihat adegan Amrozi yang selalu tersenyum bahkan saat menghitung hari dieksekusi mati. Label The Smiling Assassin ditempelkan pada sosoknya. Pakar bahasa bilang, dalam thesaurus Inggris tidak ada kata yang mewakili cengengesan. Dalam bahasa lokal Tegal, asal saya, ada istilah crengas-crenges.
Masyarakat Tak Berbaju
Salahkah jika lalu kita teringat senyuman-senyum para ODGJ yang lalu lalang di jalan tanpa pakaian? Sejak lama Mochtar Lubis mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia dihinggapi tersingkirnya budaya malu, seperti masyarakat telanjang. Masyarakat tak berbaju.
Jika ada satu onde-onde tersisa dalam jamuan tamu. Mungkin ini indikator kecil kesadaran masih perlunya rasa malu. Konon, untuk membuat onde-ode yang renyah, tidak bantat dengan adonan kacang hijau yang maknyus, serta dengan tatanan wijen yang artistik diperlukan cara menggoreng yang tepat. Suhunya harus hangat dengan takaran yang pas. Strateginya adalah jangan sampai digoreng dengan minyak yang kurang. Si onde-onde harus tenggelam dalam kubangan minyak yang cukup.
Yang jadi masalah adalah minyak goreng. Saya mengalami sendiri, mampir ke beberapa swalayan dan warung sekadar mencari kemasan 1 liter. Kebutuhan kami tak banyak. Istri saya bekerja di luar rumah, sehingga tak tiap hari masak. Minyak goreng bagi kami, sekadar untuk sesekali membuat telor ceplok untuk sarapan pagi. Kadang malam untuk menghangatkan makanan. Faktanya : minyak goreng dicari tak ada.
Ini bukanlah mitos atau cerita-cerita jenaka. Seperti kisah onde-onde yang disampaikan Pak Kastolani, guru SD yang menggugah jiwa hubbul wathan anak-didiknya. Mungkin yang habis bukan minyaknya. Tetapi habisnya tabungan rasa malu. Siapa yang menimbun berton-ton minyak hingga rakyat harus antri. Membuat para pejabat sibuk razia harga dan stok minyak goreng di negeri juragan kelapa sawit.
Di antara berita-berita tentang hadirnya MotoGP Mandalika, ribut-ribut tentang IKN, kasak-kusuk tentang pemilu, bermacam survey calon pemimpin bangsa, ternyata sulit mendapatkan minyak goreng justru membuat saya tak mau berpikir berbelit-belit. Mungkin penyebab budaya dan mentalitas yang cengengesan dan tak lagi punya malu. Nilai-nilai anti keserakahan dan merasa malu itu penting. Seperti halnya menyisakan onde-onde terakhir di piring.
Apakah rasa malu kita sudah kering? Lalu ke mana onde-onde terakhir, minyak goreng dan tepatnya rasa malu itu minggat? Barangkali pendidikan ini harus di-restart. Mulai lagi dari nol, dengan mendidik pentingnya budaya malu.
Sumber : https://kumparan.com/
Latest
Harga Naik, Daya Beli Masyarakat Turun
Pencemaran Lindi TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu ke Sungai Cijambe, Bekasi
Kok Kamu Sok Tahu?
Onde-Onde Terakhir & Budaya Malu
Gerakan Literasi Tidak Cukup Hanya Diseminarkan, Kenapa?